Peradaban abad ke sembilan belas tidak hancur karena serangan internasional atau karena ulah kaum barbar. semangatnya untuk bertahan hidup tidak berhasil dilemahkan oleh kehancuran total perang dunia I atau oleh pemberontakan kelas proletariat sosialis atau kelas menengah ke bawah yang berhaluan fasis. Kegagalannya bukanlah hasil dari apa yang dianggap sebagai hukum-hukum ekonomi seperti hukum-hukum pendapatan yang makin menurun, konsumsi yang rendah atau produksi yang berlebihan.
Keruntuhan peradaban abad ke 19 merupakan hasil dari seperangkat penyebab yang benar-benar berbeda; yakni tindakan-tindakan yang diambil oleh masyarakat dalam pergaulan ekonomi pasar, justru dimusnahkan oleh tindakan-tindakan pasar swasta karena faktor kepemilikan modal (kapital). Selain kondisi yang luar biasa yang terjadi di Amerika Utara selama masa keterbukaan perbatasan, konflik antar pasar dengan persyaratan yang mendasar bagi kehidupan sosial yang terorganisir, yang kemudian turut menyumbangkan dinamika kepada perjalanan abad ke 19 yang berujung pada ketegangan-ketegangan dan berbagai tekanan yang pada akhirnya menghancurkan masyarakat tersebut. Perang-perang eksternal hanya mempercepat proses kehancuran.
namun sejalan dengan perkembangan pengetahuan manusia, dan setelah satu abad “kemajuan” yang membabi buta manusia kini memulihkan “tempat tinggalnya” Jika industrialisme tidak ingin memadamkan perlombaan, industrialisme harus disubordinasikan terhadap prasyarat-prasyarat bagi manusia. Kritik yang sesungguhnya terhadap masyarakat pasar bukanlah bahwa masyarakat pasar didasarkan pada ilmu ekonomi—dalam beberapa hal, semua dan setiap masyarakat harus didasarkan padanya—namun bahwa sistem ekonominya didasarkan pada kepentingan pribadi (self-interest).
Pengaturan kehidupan ekonomi semacam ini benar-benar tidak murni, dan sangat empiris. Sehingga pemikir abad 19 mengasumsikan bahwa kalau kehidupan manusia dalam ekonominya hanya bekerja keras demi keuntungan semata, bahwa kecendrungan-kecendungan materialistis adalah upaya memenuhi standar kehidupan yang layak. Bahwa kemudian upaya itu tidak dapat dilepaskan dari pengaruh luar yang boleh jadi pengendali ekonomi—pengusaha dan penguasa, bisa jadi.
Selanjutnya, pasar adalah institusi yang alami; bahwa pasar akan secara spontan timbul hanya bila manusia dibiarkan sendiri. Jadi, tidak ada yang lebih normal dibandingkan sebuah sistem ekonomi yang terdiri dari pasar-pasar dan berada di bawah kendali tunggal pemilik modal (kaum borjuasi), sehingga dengan begitu sebuah masyarakat manusia yang didasarkan pada pasar-pasar semacam itu nampak sebagai tujuan dari segala kemajuan. Sehingga apa pun landasan moral bagi yang diinginkan atau tidaknya masyarakat semacam itu, tergantung kemampuannya untuk dapat dijalankan—bisa dipastikan—dilandaskan kepada karakteristik umat manusia yang tidak berubah (Karl Polanyi, 336, The Great Tranformation)
Sebenarnya, sebagaimana yang kita ketahui sekarang, tingkah laku manusia baik yang primitif maupun yang dalam sepanjang perjalanan sejarah hampir selalu berkebalikan dengan apa yang disimpulkan dalam pandangan tersebut. Pendapat Frank H. Knight bahwa “tidak ada motif manusia yang secara khusus bersifat ekonomis” yang berlaku tidak hanya pada kehidupan sosial secara umum, namun bahkan terhadap kehidupan ekonomi itu sendiri. Bahkan kecendrungan untuk melakukan barter yang secara meyakinkan digunakan ekonom klasik Adam Smith sebagai landasan untuk memberikan gambaran tentang manusia primitif, bukanlah kecendrungan umum umat manusia dalam aktivitas-aktivitas ekonominya, melainkan sebuah kecendrungan yang paling jarang terjadi.
Bukti yang diberikan antropologi tidak hanya berlawanan dengan konstruk-konstruk rasionalistis tersebut, namun sejarah perdagangan dan pasar sama sekali berbeda dengan apa yang diasumsikan dalam ajaran-ajaran yang serba harmonis dari para sosiologiwan pada abad ke sembilan belas.
Sejarah ekonomi mengungkapkan bahwa kemunculan pasar-pasar nasional sama sekali bukan hasil dari pembebasan wilayah ekonomi dari kontrol pemerintah secara bertahap dan spontan. Sebaliknya, pasar merupakan hasil sebuah intervensi secara sadar dan kadang secara paksa dari pemerintah yang memaksakan pengaturan pasar terhadap masyarakat, demi tujuan-tujuan nonekonomi. Dan bila diperhatikan lebih dekat pasar swasta pada abad ke sembilan belas bahkan berbeda jauh, bahkan dengan pendahulunya yang baru saja digantikannya dalam hal “ketergantungan” pada kepentingan ekonomi pribadi termasuk dalam pengaturan sirkulasi pasar.
“Kelemahan bawaan masyarakat abad ke sembilan belas, bukan apakah tatanan tersebut memiliki sifat-sifat industri namun bahwa tatanan tersebut adalah sebuah masyarakat pasar” Meskipun begitu mengubah peradaban industri menuju sesuatu yang baru dengan landasan aktivitas non-pemasaran (non marketing basis) akan menjadi jalan lain untuk menemukan esensi tata kelolah ekonomi dunia. Sehingga manusia dan pasar adalah simbiosis-mutualisme—ada pekerja, buruh, dan ada penyedia dalam hal ini pengusaha (pemilik modal).
Misalnya, relasi sosial dalam pandangan Marx, yang menginginkan adanya kesetaraan manusia yang disebut dengan “masyarakat egalitarian” yakni sebuah masyarakat tanpa kelas, persamaan hak-hak individu menjadi epicentrum dari pergaulan antarmanusia. Relasi sosial itu pada akhirnya, dalam pandangan Marx mendorong upaya terjadinya revolusi sosial yang berhadapan antara “kaum proletariat dan kaum borjuasi”
Perspektif Marx, tentang masyarakat kesetaraan (Egaliter) adalah upaya menghindari monopoli ekonomi pasar, dan penguasaan sektor-sektor ekonomi oleh kelompok dan individu tertentu. Sebab beberapa pandangan sosiolog mengungkapkan bahwa, tujuan aktivitas ekonomi adalah untuk pemenuhan kebutuhan hidup, kesejahteraan serta kesetaraan sosial di antara manusia.
Manusia dan relasi sosialnya
Karl Polanyi dalam karyanya “The Great Tranformation; The Political and Social Origins Of Our Time” tahun 1944 yang terbit di Boston, Amerika Serikat, sekali lagi, kehancuran peradaban abad ke sembilan belas sangat diakibatkan oleh munculnya kecendrungan penguasaan ekonomi pasar yang dikendalikan oleh individu dan kelompok tertentu, terhadap penguasaan kelompok manusia lainnya. Relasi sosial itu terkesan hubungan antara kaum pemilik modal dengan kaum pekerja (buruh)---sebagian para kritikus melihat relasi ini sebagai relasi antar penindas dengan yang ditindas.
Tetapi menurut Polanyi, transformasi besar itu bukan hanya sebatas memotret relasi manusia dalam aktivitas ekonomi atau pertukaran nilai (barang dan jasa) dalam struktur kehidupan masyarakat, tetapi transformasi besar itu adalah adanya upaya pergeseran pola hubungan masyarakat. Terlihat dalam pikiran Polanyi, disebutkannya “ekonomi politik dan ditemukannya masyarakat” –munculnya kredo liberal dalam praktek ekonomi baru, dan bagaimana relasi pasar dan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan sistem pengaturan produksi, yang dianggap menjadi centra-point dari pikiran Polanyi atas kehancuran peradaban abad ke sembilan belas.
Dalam perspektif yang lain, Kenichi Ohmae dalam bukunya “The End of The Nation State; The rise of regional economics” yang melihat kondisi bangsa yang berada di titik kehancuran, yang dilukiskan adanya berbagai gejolak ekonomi regional dalam negara; seperti pajak, distribusi produksi yang timpang, PHK yang meningkat, angka pengangguran yang tak terkendali, korupsi, illegal mining, illegal fishing, kelangkaan sumber-sumber mineral, dan krisis ekologis. Ohmae memandang, kalau semua itu menjadi sumber ketegangan dalam negara, kritik, serta aksi protes sulit untuk dibendung ketika negara abai pada soal-soal kebutuhan primer masyarakat. Ekonomi regional, termasuk kemampuan fiskal di dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak. Kondisi fiskal pada skala ekonomi regional tentu sangat berpengaruh pada suistanable development (Pembangunan berkelanjutan).
Kekhawatiran Ohmae cukup beralasan, mengingat peran penting negara di dalam mengartikulasikan kepentingan warga negara yang (mungkin) belum selesai. Political policy, menjadi penting untuk negara mengambil sikap untuk menyelamatkan negara dalam kehancuran. Potensi kehancuran itu terlihat dengan berbagai angka korupsi di beberapa negara berkembang (dunia ketiga) termasuk Indonesia.
Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam satu bukunyayang berjudul “Mengapa Negara gagal”—Why Nations Fail; Awal mula kekuasaan, kemakmuran dan kemiskinan” menjelaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu negara dalam mencapai kemakmuran dan stabilitas jangka panjang sangat bergantung pada jenis lembaga politik dan ekonomi yang dibangunnya. Bahwa negara-negara yang memiliki lembaga inklusif cenderung makmur, sementara negara dengan lembaga ekstraktif cenderung terjerumus dalam kemiskinan dan konflik.
Lembaga-lembaga yang inklusif adalah lembaga yang memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara, mendorong partisipasi politik, melindungi hak milik, dan menjamin supremasi hukum. Sedangkan lembaga-lembaga ekstraktif adalah lembaga yang memusatkan kekuasaan dan kekayaan pada segelintir elite, mengeksploitasi sumber daya dan tenaga kerja untuk kepentingan mereka sendiri, dan tidak memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga.
Adapun contoh-contoh sejarah dari berbagai negara dan peradaban (seperti Roma, Maya, Venesia, Uni Soviet, Amerika Latin, Inggris, AS, dan Afrika) untuk menunjukkan bagaimana perbedaan dalam membangun lembaga politik dan ekonomi telah membentuk nasib negara-negara tersebut. tetapi bukan hanya pada aspek historis. tetapi Acemoglu juga mengkritik beberapa teori lain yang mencoba menjelaskan mengapa negara gagal, seperti teori iklim, geografi, dan budaya, dan berpendapat bahwa faktor-faktor tersebut tidak cukup untuk menjelaskan perbedaan besar dalam kemakmuran antar negara.
Berangkat dari beberapa pandangan tersebut di atas, negara dunia ketiga juga menjadi sorotan bukan hanya pada tatanan pembangunan ekonomi semata, tetapi juga pada sapek demokrasi, hukum, sosial dan politik menjadi catatan penting untuk melihat pakah negara tersebut survive ataukah menuju kehancuran. Perang Iran-Israel, India-Pakistan, Rusia-Ukraina, Thailand-Kambodja—menjadi variabel penting bagi situasi keberlanjutan pembangunan di belahan dunia ketiga (negara berkembang). Termasuk perang dagang Amerika dengan Tiongkok juga memberi dampak serius bagi pembangunan eknomi di kawasan dunia ketiga. Indonesia menjadi penting di kawasan dunia ketiga---di negara ini memang tidak terjadi konflik bersenjata dengan negara lain, tetapi “musuh dalam negara” seperti korupsi yang terus meningkat, kecurangan dalam pemilu (proses politik), supremasi hukum yang lemah, political trial, dan pengrusakan pada sektor ekologis—menjadi ancaman serius bagi Indonesia di kawasan Asia tenggara.
Bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif hanya dapat dicapai melalui pembentukan lembaga-lembaga politik dan ekonomi yang inklusif. Sehingga secara keseluruhan, "Why Nations Fail" menawarkan perspektif baru tentang pembangunan ekonomi dan politik, dengan menyoroti pentingnya institusi dalam menentukan nasib suatu negara. Bila initidak menjadi perhatian serius bagi pengambil kebijakan di negeri ini maka tidak tertutup kemungkinan “kehancuran” menjadi keniscayaan.
Oleh: Saifuddin
Direktur Eksekutif LKiS
Dosen, Peneliti, Penulis buku, kritikus sosial politik, dan penggiat demokrasi.
______________________________________
Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan GELORA.ME terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi GELORA.ME akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.




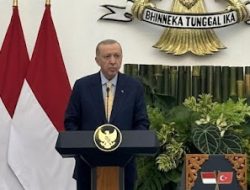

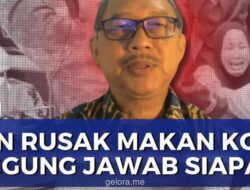




Artikel Terkait
SD Negeri 64 Ambon Resmi Ditetapkan sebagai Sekolah Ramah Anak
Pelajar Tewas Kecelakaan Diduga Akibat Lubang Jalan di Matraman
Pemerintah Rancang Perpres Penghapusan Tunggakan BPJS Kesehatan Kelas 3
BI Proyeksikan Ekonomi Jakarta Tumbuh 4,8-5,6% pada 2026, Konsumsi Jadi Penopang