Populisme, Pencitraan, dan Otoriter: 'Membandingkan KDM dan Jokowi Dalam Konteks Demokrasi'
Oleh: Radhar Tribaskoro
Dedi Mulyadi atau akrab disebut KDM, menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dengan gaya kepemimpinan yang mencolok dan kontroversial.
Banyak pihak menyebutnya mirip dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), bahkan menuduhnya sebagai jiplakan.
Tuduhan lain menyebut KDM sebagai pemimpin populis dengan kecenderungan otoriter.
Dalam tulisan ini, saya ingin mengulas secara lebih ilmiah dua hal: apakah benar KDM hanya meniru Jokowi, dan apakah langkah-langkah langsung dan tegas yang ia ambil menandakan sifat otoritarian?
Dengan merujuk pada teori populisme, demokrasi substantif, dan otoritarianisme kompetitif, kita akan mencoba menempatkan KDM dalam spektrum kepemimpinan kontemporer Indonesia.
Populisme: Istilah yang Perlu Didefinisikan Ulang
Secara akademik, populisme bukanlah kata negatif, meskipun kerap digunakan sebagai celaan dalam diskursus publik.
Menurut Cas Mudde (2004), populisme adalah ideologi tipis (thin-centered ideology) yang melihat masyarakat terbelah menjadi dua kelompok homogen: rakyat murni versus elite korup.
Dalam konteks ini, pemimpin populis sering kali mengklaim diri sebagai perwakilan langsung dari rakyat, memotong jalur institusional untuk memberikan solusi cepat dan konkret.
Baik Jokowi maupun KDM bisa disebut populis dalam pengertian ini. Namun ada perbedaan fundamental dalam cara keduanya mengekspresikan populisme:
- Jokowi dikenal dengan gaya kepemimpinan simbolik: blusukan, komunikasi publik yang lembut, dan strategi pencitraan yang kuat sejak kampanye 2014.
Namun seiring berjalannya waktu, Jokowi semakin banyak menyesuaikan diri dengan elite partai dan oligarki ekonomi, memperlihatkan kompromi dengan kekuasaan terpusat.
- KDM, sebaliknya, justru muncul sebagai antitesis dari kompromi politik. Ia mendobrak sistem dari dalam, memilih jalan langsung—kadang sendirian—dalam mengeksekusi kebijakan.
Ia membongkar beton sungai, menertibkan pasar, bahkan mengirim siswa bermasalah ke pusat pelatihan militer. Ia tak segan menggunakan uang pribadi untuk mengatasi masalah kemanusiaan. Semuanya ditampilkan di media sosial secara transparan.
Keduanya menggunakan media sosial, tetapi KDM menggunakannya bukan hanya untuk pencitraan, melainkan sebagai ruang pertanggungjawaban langsung ke publik.
Jokowi memposisikan diri sebagai presiden yang mewakili stabilitas dan harmoni. KDM menampilkan diri sebagai pemimpin yang tegas, kadang konfrontatif, tetapi akuntabel.
Media Sosial: Panggung Demokrasi Baru
Perbandingan ini menjadi penting karena media sosial telah menjadi arena baru demokrasi deliberatif.
Dalam kerangka pemikiran Manuel Castells (2009), kita memasuki era networked politics, di mana hubungan langsung antara pemimpin dan rakyat dimediasi oleh teknologi digital.
Ini menciptakan jenis baru dari legitimasi, yang tidak hanya berdasarkan prosedur (prosedural) tetapi berdasarkan partisipasi visual dan responsif.
Di sinilah kita melihat perbedaan mencolok:
- Jokowi cenderung menampilkan visualisasi stabilitas, kunjungan kerja, dan penegasan peran negara.
- KDM menggunakan media sosial sebagai instrumen untuk memetakan masalah, menunjukkan proses, dan membuka ruang koreksi publik secara real time.
Dengan demikian, menyebut KDM sebagai “jiplakan Jokowi” karena sama-sama menggunakan media sosial tidaklah adil.
KDM menampilkan aksi bukan pose. Gaya komunikasinya bukan penggambaran kekuasaan, melainkan transparansi kerja.
Apakah KDM Otoriter?
Tuduhan otoritarianisme sering dialamatkan kepada KDM oleh kalangan LSM dan partai politik. Namun jika kita kembali pada definisi ilmiah, otoritarianisme melibatkan beberapa elemen:
- - Konsentrasi kekuasaan yang tidak terbagi.
- - Penghapusan atau pembatasan lembaga oposisi.
- - Penggunaan instrumen negara untuk menekan kritik.
- - Represi terhadap kebebasan sipil.
KDM, sejauh ini, tidak menunjukkan indikator-indikator di atas. Ia justru mempraktikkan keterbukaan tinggi dalam komunikasi publik.
Ia tak mengintervensi pemilu, tak membungkam DPRD secara institusional, dan tak menggunakan aparat untuk menekan kritik.
Ia bahkan menerima kritik terbuka dan menjawabnya langsung di media sosial.
Pengiriman siswa bermasalah ke pendidikan militer memang menuai kritik.
Namun langkah itu bukanlah tindakan koersif sistematis, melainkan bentuk intervensi sosial berbasis kedisiplinan.
Bahkan, banyak dari siswa itu mendapat pembiayaan pribadi dari sang gubernur.
Dalam konteks ini, tindakan KDM lebih mencerminkan bentuk governing by example daripada governing by fear.
Steven Levitsky dan Lucan Way (2010) menyebut istilah competitive authoritarianism untuk rezim yang tampak demokratis namun sebenarnya menggunakan institusi formal untuk mempertahankan kekuasaan. Dalam pengamatan terhadap KDM, tidak terlihat adanya pola tersebut.
Ia tidak menggunakan kekuasaan untuk mengamankan posisinya, justru berani menghadapi risiko politik dengan gaya kerja yang tidak populer di kalangan elite.
Legitimasi: Prosedural vs Kinerja
Konflik antara KDM dan DPRD Jawa Barat mencerminkan konflik klasik antara dua jenis legitimasi:
- Legitimasi prosedural: diperoleh dari pemenuhan aturan formal dan mekanisme koordinasi.
- Legitimasi kinerja (performance legitimacy): diperoleh dari hasil konkret yang dirasakan rakyat.
KDM mengambil risiko dengan memprioritaskan yang kedua. Ia tidak mengabaikan prosedur, tetapi mempercepatnya atau menempuh jalur alternatif ketika prosedur justru menjadi alat untuk menunda atau menumpuk kepentingan.
Dalam teori new public management (Osborne & Gaebler, 1992), tindakan seperti KDM dianggap sah dan perlu, khususnya dalam konteks stagnasi birokrasi.
Model kepemimpinan seperti ini muncul ketika birokrasi tidak lagi bisa menjawab kebutuhan publik dengan cepat.
Kritik terhadap KDM: Perlu Teoretisasi, Bukan Delegitimasi
Sebagian kritik terhadap KDM muncul karena cara kerjanya yang tidak konvensional dianggap merusak tatanan.
Namun justru di sinilah letak tantangan intelektual kita: perlu teoretisasi terhadap gaya kerja seperti ini agar tidak dikurung dalam label populis, otoriter, atau pencitraan semata.
KDM bisa dibaca dalam kerangka “disruptive bureaucrat”, yakni pemimpin yang menantang tata kelola lama tetapi tetap bertanggung jawab secara publik.
Ia tidak menciptakan sistem paralel, tetapi memperbaiki sistem melalui tekanan moral dan kerja nyata.
Dalam konteks Luhmannian, KDM bisa dipahami sebagai “irritasi positif” terhadap sistem politik yang tertutup.
Ia membawa diferensiasi baru—menginjeksikan logika kemanusiaan ke dalam sistem formal yang selama ini terlalu mekanistik.
Penutup: Demokrasi Butuh Eksperimen
KDM bukanlah Jokowi kedua. Ia bukan populis dangkal. Ia bukan pula otoriter.
Ia adalah representasi dari eksperimen baru dalam kepemimpinan daerah: langsung, transparan, efektif, dan tak segan bertanggung jawab secara pribadi.
Bahwa ia kontroversial, itu wajar. Setiap bentuk inovasi dalam politik selalu menimbulkan resistensi dari sistem lama.
Namun jika kita ingin demokrasi tumbuh bukan hanya dalam bentuk prosedur tetapi dalam hasil yang nyata, maka model-model kepemimpinan seperti KDM layak mendapatkan ruang.
Bukan untuk dikultuskan, tapi untuk dipelajari dan dikritisi secara ilmiah—bukan secara emosional atau partisan. ***

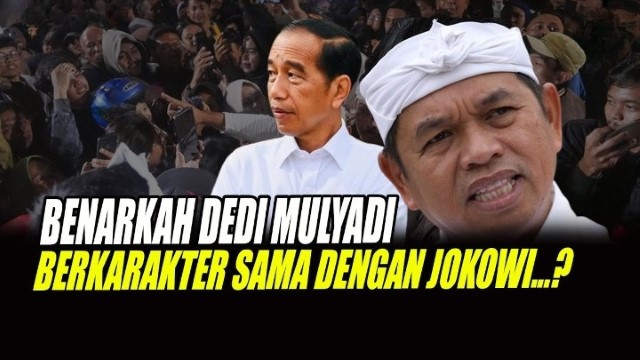




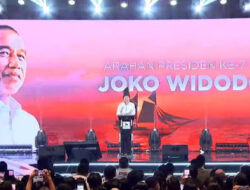




Artikel Terkait
Dokumen Jeffrey Epstein Dibuka: Nama Elon Musk, Pangeran Andrew, hingga Sergey Brin Terungkap
Iran Siapkan Ribuan Kuburan Massal untuk Tentara AS: Persiapan Perang Terbuka?
Santunan Rp15 Juta dari Mensos untuk Ahli Waris Korban Tewas Banjir Sumatra
Puslabfor Polri Ungkap Bercak Darah di Kamar Lula Lahfah: Hasil Analisis Forensik Lengkap